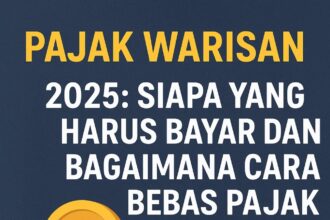Haloklbar.com
Kebijakan pertambangan di Indonesia kerap menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah dan korporasi memandang sektor ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, dengan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah.
Namun, di sisi lain, masyarakat lokal—terutama mereka yang hidup di sekitar area pertambangan—justru menanggung beban paling berat dari kebijakan ini, seringkali dengan dampak yang jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Pendapat umum seringkali berfokus pada dampak positif pertambangan yang kasat mata: lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jalan-jalan baru yang mulus, jembatan yang kokoh, atau fasilitas kesehatan yang dibangun oleh perusahaan tambang seolah menjadi bukti nyata dari janji kemakmuran. Bagi sebagian masyarakat, ini adalah kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dengan bekerja di sektor formal atau membuka usaha kecil yang menopang operasional tambang.
Namun, narasi tersebut seringkali mengabaikan dampak negatif yang lebih dalam dan sistemik. Kerusakan lingkungan adalah isu yang paling mendesak. Pembukaan lahan besar-besaran, pencemaran air akibat limbah, dan deforestasi merusak ekosistem yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Alih-alih mendapatkan manfaat, mereka justru kehilangan sawah, ladang, atau area tangkap ikan. Lubang-lubang galian yang dibiarkan begitu saja menjadi jebakan maut dan sarang penyakit.
Selain itu, pertambangan juga menjadi pemicu konflik sosial yang rumit. Sengketa lahan, kompensasi yang tidak adil, dan masuknya pekerja dari luar daerah seringkali menciptakan ketegangan yang memecah belah komunitas.
Masyarakat yang dulunya hidup rukun kini terbelah antara yang pro dan kontra tambang, bahkan tak jarang harus berhadapan dengan intimidasi dari pihak-pihak yang berkuasa.
Yang paling mengkhawatirkan adalah ketergantungan ekonomi yang diciptakan oleh sektor ini. Saat tambang beroperasi, masyarakat meninggalkan pekerjaan tradisional mereka, seperti bertani atau melaut. Ketika sumber daya habis dan tambang ditutup, mereka ditinggalkan dengan tanah yang rusak dan tanpa keahlian lain, berujung pada pengangguran massal dan kemiskinan yang lebih parah.
Pemerintah pusat perlu meninjau kembali kebijakan pertambangan dengan perspektif yang lebih adil dan berimbang. Keuntungan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat lokal.
Sudah saatnya kita tidak hanya berbicara tentang royalti dan pajak, tetapi juga tentang tanggung jawab, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Sebuah kebijakan pertambangan yang sejati harus mampu menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam, bukan sekadar memindahkan kekayaan dari perut bumi ke segelintir kantong, sementara sisanya menanggung buntungnya.
Sumber : Haloklbar.com